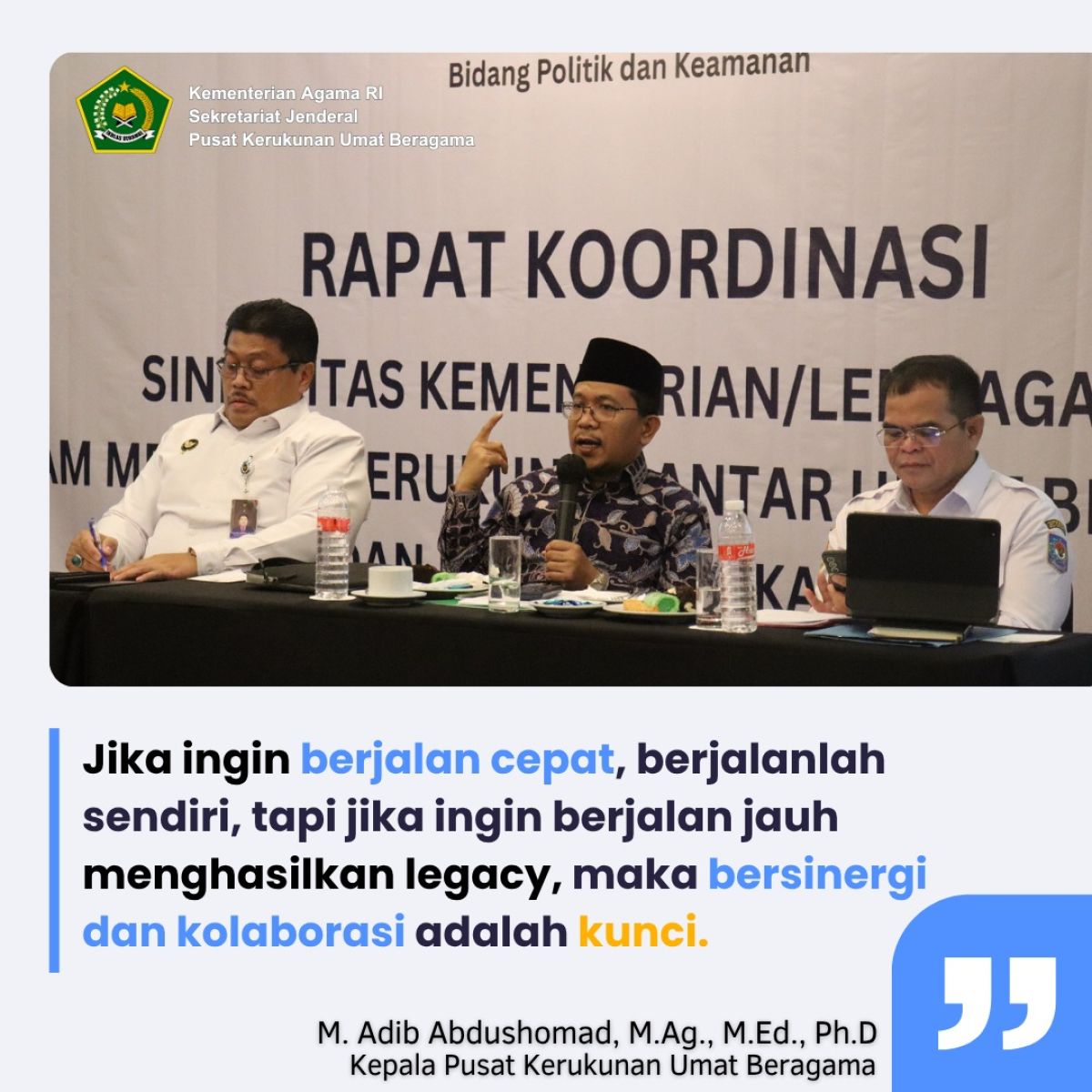M. Hafidzulloh SM
Pengajar di UIN SATU Tulungagung, Mahasiswa Doktoral Ilmu-ilmu Humaniora FIB UGM.
Kemucnulan diskursus polemik bangunan epistemologi
ilmu pengetahuan yang berlaku pada dunia Ketiga semakin mencuat. Pembahasan
dari sisi ilmu pengetahuan (epistemis disobedience) (Mignolo, 2009),
wawasan agama yang disertai dengan seluk-beluk dinamikanya (Hefner, 2023;
Woodward, 2024) telah mewarnai konstelasi apa dan mengapa penting pembahasan
dekolonial itu perlu diwujudkan.
Pertama saya akan sedikit memberi gambaran tentang apa urgensi pembahasan di atas? Ketika dunia
ketiga salah satunya adalah Indonesia, mencoba untuk mencari afirmasi pada
dimensi ilmu pengetahuan senantiasa berlindung di bawah payung sarjana Barat.
Kecenderungan ini bukan menjadi rahasia lagi; terlihat seperti glorifikasi
bangunan epistemologi Barat, menjadikannya sebagai sandaran, serta diposisikan
pada piramida tertinggi dalam koridor saintifik. Barangkali asumsi ini agak
berlebihan ketika dihadapkan pada suatu mekanisme kontrol akademik, tetapi
kondisi inilah yang hari ini terjadi. Bahkan sistematika yang hari ini
dikonstruksi sebagai “yang ideal” ternyata adalah bagian dari kontrol epistemik
dalam menggapai kepadanan yang bersifat universal.
Kedua, persoalan lain yang layak untuk dihadirkan
dalam persoalan dekolonialisasi bergerak pada ranah alasan yang digunakan
sebagai dasar untuk menyatakan geliat terhadap proyeksinya. Telaah Popper (1959)
dalam menyoal adanya mekanisme falsifikasi terhadap suatu bangunan epistemik
bisa digunakan sebagai dasar untuk mengonfirmasi adanya suatu kejanggalan yang
senantiasa hadir pada tata epistemik yang selama ini telah tertata (established).
Kecurigaan ini perlu digaungkan sebagai jalan untuk menemukan, paling tidak,
menawarkan suatu gugusan yang selama ini tidak pernah tersentuh sama sekali.
Maka, tidak menjadi suatu kondisi yang penuh
kejanggalan pada saat apresiasi yang terlalu berlebihan lebih melekat pada tata
epistemik sesuai dengan dimana kehidupan itu berlangsung. Dengan arti bahwa
setiap glorifikasi yang tidak karuan akan berdampak pada pemosisian secara
hierarkis, suatu kondisi dengan penuh dengan kebanggan akan suatu karya
masterpiece yang itu sama sekali berasal bukan dari diri sendiri; falsafah
kehidupan, kebudayaan, hingga nilai kultural yang (sengaja) dihilangkan untuk
menggemakan epistemologi yang lain.
Tawaran ini tidak lain ihwal yang berkaitan dengan
tata paradigma yang berlaku saat ini semakin jelas ke arah sentrifugal, dimana
pergerakan itu mulai menjauh dan ketidaksadaran adalah bagian yang tidak
terpisahkan. Apa yang kemudian menjadi fokus dalam membentuk suatu
keterpengaruhan ini tidak lain karena proyek universalisasi yang semakin
menguat sebagai jalan tol untuk menyandarkan diri sebagai bagian kelompok yang
lebih besar. Oleh karena itu, alternatif lain yang perlu diperjelas adalah
mengapa obskur kultural ini diperlukan sebagai pembahasan untuk menguak sistem
yang sebelumnya telah tertata dengan sempurna dan menghadirkannya kembali dalam
tata epistemik yang lebih kontekstual.
Alternatif Lain
Agaknya, istilah pembangkangan landasan epistemik (epistemic
disobedience) sedikit mengundang kecurigaan terhadap unifikasi,
universalisasi, dan homogenisasi sebagai mekanisme kontrol. Salah satu sosiolog
Perancis, Pierre Bourdieu (2007), melontarkan tesis bahwa kuasa simbolik
berperan penting dalam membentuk struktur kehidupan diarahkan pada satu titik
tertentu; operasi ini dilakukan dengan kontrol terhadap segenap aktifitas
kultural yang dianggap sebagai tatanan ideal. Akibatnya, apa yang selama ini
dianggap sebagai bagian dari norma ideal, nyatanya, tidak lain merupakan
obskuritas yang telah termodifikasi dengan sempurna. Apriori, dengan demikian,
tidak lain sebagai alternatif untuk mencari suatu legitimasi, meski masih pada
bayang-bayang imajinatif.
Pluriversalitas, pada sisi yang lain, sebagaimana
yang disampaikan Mignolo, merupakan alternatif untuk menginisuasi kondisi
masyarakat yang berada di bawah tekanan kuasa simbolik. Dengan memberi
penekanan terhadap pluriveralitas—serangkaian proses untuk menggali, menemukan,
dan mengaktualisasikan tata epistemik internal, guna memproyeksikan tata
epistemik yang tidak latah dan mengekor dari gugusan nilai eksternal.
Dalam banyak hal, pluriversalitas menginisuasi
persoalan ketidaksadaran yang selama ini terus direproduksi secara kontinyu.
Sebagai contoh bagaimana pluriversalitas itu mewujud dalam struktur kebudayaan
bisa dilihat masyarakat Jawa yang telah memprediksi suatu keadaan dunia dan
segala tata isinya semakin tidak menentu. Dalam serat Kalatidha, salah satu
karya fonemonal yang ditulis oleh Ronggowarsito, telah menawarkan suatu konsep
dimana kehidupan duniawi semakin runyam, baik dari sisi tata sosial maupun lingkungan.
Serat tersebut, setidaknya, menawarkan suatu
konsepsi akan kehidupan manusia yang semakin diposisikan sebaga sentral dalam
semua lini. Akibatnya, logika untuk bisa menguasai adalah bagian integral yang
melekat dalam diri manusia. Inilah kondisi dimana subjek modern menubuh dalam
diri manusia. Maka, tidaklah menjadi suatu kemustahilan ketika perbincangan
mengenai ekologi, misalnya, menempati strata yang sering dijadikan isu global.
Jauh sebelum teoretisasi ekologi itu menjadi dominan, kontekstualisasi serat Kalatidha
sebagai manifestasi produk kebudayaan telah mewujud secara spekulatif yang
memungkinan untuk dikontekstualisasikan untuk hari ini.
Sebagai refleksi kritis, jalan lain dari apresiasi
terhadap pluriversalitas adalah kesadaran akan nilai yang sebelumnya telah
menjadi bagian dari paradigma lokalitas. Tidaklah menjadi anomali ketika
lokalitas yang selama ini terkubur dalam dibangkitkan kembali sebagai
manifestasi nilai yang penuh dengan landasan filosofis. Akhirnya,
pluriversalitas menghendaki adanya epistem lokalitas yang bisa menjadi
preferensi dalam menjangkau tata epistemik yang lebih dibutuhkan dan
diaktualisasikan sebagai way of thinking seni bernalar