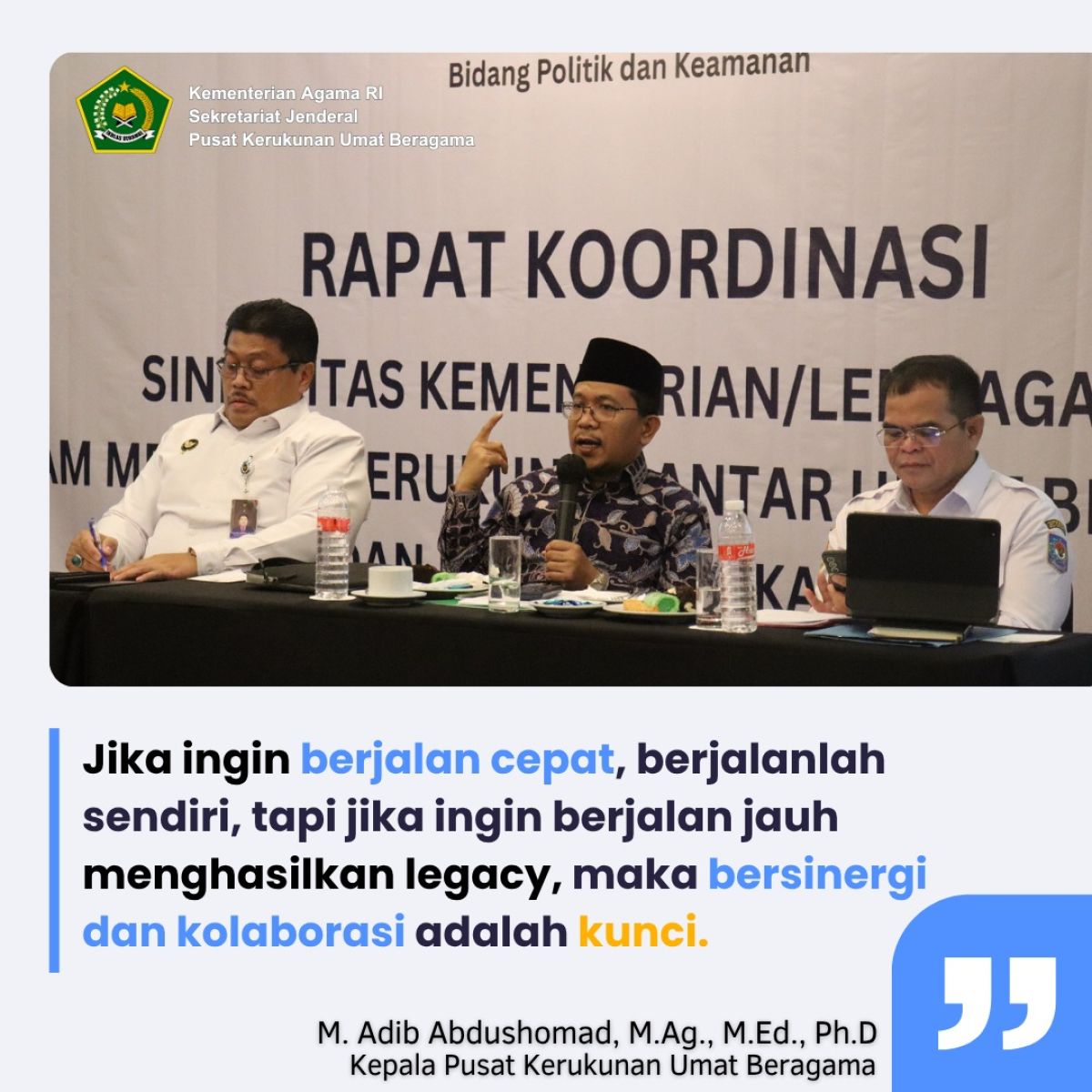Adib Khairil
Musthafa
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Kuntowijoyo, lewat karyanya “Muslim Tanpa Masjid” (2001) sekilas menampakkan sebuah “ramalan” terhadap fenomena kemunculan otoritas agama baru (new religious authority). Gejala otoritas agama baru bernama digital-religious athority itu terlihat setidaknya dalam beberapa dekade terkahir.
Meskipun tampak permukaan kemunculan otoritas baru ini memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses informasi dan pengetahuan keagamaan tanpa harus belajar ke pesantren, madrasah atau mendatangi seorang kiai/ustaz. Namun di sisi yang lain, ia menimbulkan “paradoks” otoritas agama, sejauh mana prasyarat keagamaan normatif yang diajarkan dalam media sosial cukup “otoritatif” dan tak tercampur-aduk dengan agenda politik gerakan ideologis mereka? persoalan terakhir ini yang agaknya justru terlihat dari penampilan para influence islamis di media sosial belakangan.
Semaraknya peranan media baru seperti Youtube, Instagram, Twitter hingga TikTok dalam pergulatan wacana keagamaan baru-baru ini telah memunculkan satu fenomena baru: Digital-Islamism, lengkap dengan beragam modus, atribut ideologis dan gaya retorika kekiniannya.
Ekosistem Ideologis
Kemunculan digital-citizenship memungkinkan interaksi ideologis dan wacana keagamaan berkelindan dengan perkembangan pesat media baru. Meski sekilas kemunculan media baru dapat dibaca sebagai bagian dari perkembangan ruang publik masyarakat muslim yang semakin terbuka. Namun agenda Islam Politik perlu dilihat tidak saja sebagai “insiden terisolasi” belaka. Ia juga penting dilihat sebagai gejala dari munculnya gerakan metamorfosis digital Islam Politik sebagaimana kekhawatiran opini Faiz berjudul “Metamorfosis Digital HTI” (Kompas 25/02/2025)
Pembubaran kelompok Islam politik seperti HTI pada
2017 lalu dasarnya memang tidak memberikan implikasi begitu signifikan terhadap
bersemainya pemahaman radikal di kalangan generasi muda. Riset SETARA Institute
pada 2019 terhadap sepuluh perguruan tinggi PTN menunjukkan bahwa beberapa
eks-HTI justru beralih terlibat dalam “gerakan kultural” lewat gerakan-gerakan Tarbiyah
yang diakokomodasi oleh berbagai latar identitas gerakan Islam transnasional.
Dalam kondisi semacam inilah, ruang digital ikut
serta berkerja dan terlibat sebagai medan reproduksi narasi ideologis mereka. Lewat
platform inilah kelompok Islam Politik telah jauh-jauh hari menciptakan apa
yang saya sebut sebagai “ekosistem ideologis” (ideological-ecosystem).
Siniar baru seperti Youtube, Instagram, Tiktok dan Twitter telah menjadi salah
satu arena baru mereka dalam mereproduksi wacana Islamisme.
Berbeda dengan pola tradisional yang cenderung mengandalkan struktur kelembagaan, Islamisme digital tampak menawarkan dakwah yang lebih segar, cair dan adaptif dengan segmen anak-anak muda. Mereka dengan piawai memanfaatkan retorika keagamaan Islamisme dengan gaya dakwah yang santai, trendy dan pandai membaca ceruk pasar terkini masyarakat muslim.
Sebagaimana dicatat oleh Supriansyah (2024) Islamisme
gaya baru ini cukup gigantik dalam memanfaatkan “market” ekonomi digital. Lewat
kelas-kelas berbayar, merchandise, donasi crowsfunding, hingga
fitur membership yang difasilitasi oleh berbagai platform seperti
Youtube, TikTok, Twitter hingga Instagram menjadikan sumber daya ekonomi mereka
tidak lagi (sepenuhnya) bergantung pada jejaring institusional sebagaimana
lumrahnya gerakan transnasional Islamisme di masa lalu. Namun kepiawaian mereka
sebetulnya tak cukup mampu menyembunyikan gaya dakwah mereka yang cenderung
konservatif, dogmatis dan politis.
Tidak hanya sumber daya ekonomi, ruang digital memungkinkan mereka membentuk gerakan “Islamisme yang tak kasat mata” (Imagined Islamism-community). Lewat fasilitas dan jejaring media baru, secara terselubung mereka berhasil membentuk sumber daya kultural lewat komunitas keagamaan digital yang didominasi oleh followers anak-anak muda muslim. Secara diam-diam gerakan ini berhasil menciptakan sebuah ekosistem ideologis berbasis komunitas media sosial.
Komodifikasi Dakwah Keagamaan
Pertanyaannya, mengapa dakwah mereka dapat dengan
mudah diterima? Menarik memperhatikan tesis Oky Setiana Dewi (2020) dalam disertasinya
berjudul “Penerimaan Kelas Menengah Muslim terhadap Dakwah Salafi dan Jamaah
Tabligh (2000-2019)” yang menjelaskan bahwa salah satu alasan para
informannya (kalangan selebritis) memilih kelompok Salafi-Islamis dalam belajar
agama adalah kemudahan akses terhadap konten keagamaan mereka yang tersebar
luas di media sosial.
Noorhaidi Hasan (2009) dalam “The making of public Islam: piety, agency, and commodification on the
landscape of the Indonesian public sphere” menjelaskan bahwa lewat
komodifikasi agama dakwah Islam dikemas dengan tampak lebih meyakinkan dan
mengesankan. Kepiawaian mereka dalam melakukan komodifikasi narasi keagamaan di
ruang media mampu menampilkan Islam yang dapat diterima dengan cukup mudah
terutama oleh kelas menengah muslim.
Dari dua penjelasan itu, kita dapat dengan mudah melihat betapa besarnya pengaruh media sosial terhadap preferensi, pencarian, keputusan hingga penerimaan “jenis” dakwah keagamaan di ruang digital.
Meminjam tesis Hefner (2024) kelompok Islamis memang memiliki
kecenderungan menggunakan gaya epystemological-populism (populisme-epistemologis)
ceramah keagamaan mereka memiliki corak untuk menawarkan ajaran-ajaran Islam
yang sederhana, normatif, dengan gaya yang santai tanpa menghilangkan kesan
argumentasi tekstualnya.
Kecenderungan gaya dakwah semacam itu sebetulnya dapat dibaca sebagai bagian dari upaya kelompok ini untuk tetap eksis di tengah upaya eksklusi pemerintah terhadap gerakan struktural mereka yang gagal. Kegagalan kelompok Islamis di wilayah “struktural” telah membawa peralihan gerakan mereka ke wilayah “kultural” lewat arena yang disebut Hasan (2009) sebagai “Public-Piety” (kesalehan publik). Tidak heran, gerakan-gerakan ini berulang kali bermetamorfosis dalam bentuk-bentuknya yang baru di ruang publik.
Semaraknya ruang digital dalam wacana keagamaan
belakangan, tidak absen dibaca kelompok ini sebagai medan baru mereka dalam melanjutkan
agenda masa lalu berbasis platform digital. Bedanya, jika di masa lalu, gerakan
mereka dapat dengan mudah diidentifikasi melalui penggunaan simbol-simbol Islamisme.
Lain hal dengan Islamisme-digital, mereka piawai melakukan komodifikasi dakwah
keagamaan dengan melakukan adaptasi dan kooptasi penggunaan simbol-simbol dan tren
anak muda terkini. Dalam retorika dakwah misalnya, mereka tak lagi segan
menggunakan tagline seperti toleransi, keberagaman hingga kemanusiaan
yang sebelumnya identik dengan kelompok Islam moderat. Mereka cukup piawai
menampilkan diri mereka sebagai “bagian” dari juru bicara Islam moderat.
Pertanyaannya, dapatkah kita membaca fenomena metamorfosis Islamisme itu sebagai satu gejala yang natural? Atau fenomena itu dasarnya adalah babak baru gerakan Islamisme di Indonesia?
Tidak berlebihan untuk menganggap bahwa tugas kalangan moderat sekarang jauh lebih berat dalam melawan wacana keagamaan kelompok ini. Keputusan pemerintah dengan menggunakan pendekatan struktural (top-down approach) terhadap kelompok ini dasarnya harus dibayar dengan implikasi yang cukup mahal. Kita akan tampak kesulitan mengidentifikasi gerakan-gerakan Islamisme semacam itu di ruang publik.
Program Moderasi beragama (PMB) misalnya, menemui tantangannya tersendiri, mewaspadai gerakan terselubung kelompok Islamis-fundamentalis tak mungkin dapat diselesaikan (hanya) melalui seminar-seminar seremonial program penguatan moderasi beragama. Perlu upaya komprehensif, struktural juga kultural dalam merumuskan agenda besar terhadap potensi paparan pemahaman radikal terutama di kalangan generasi muda sebagai konsumen utama konten-konten keagamaan di platform digital.